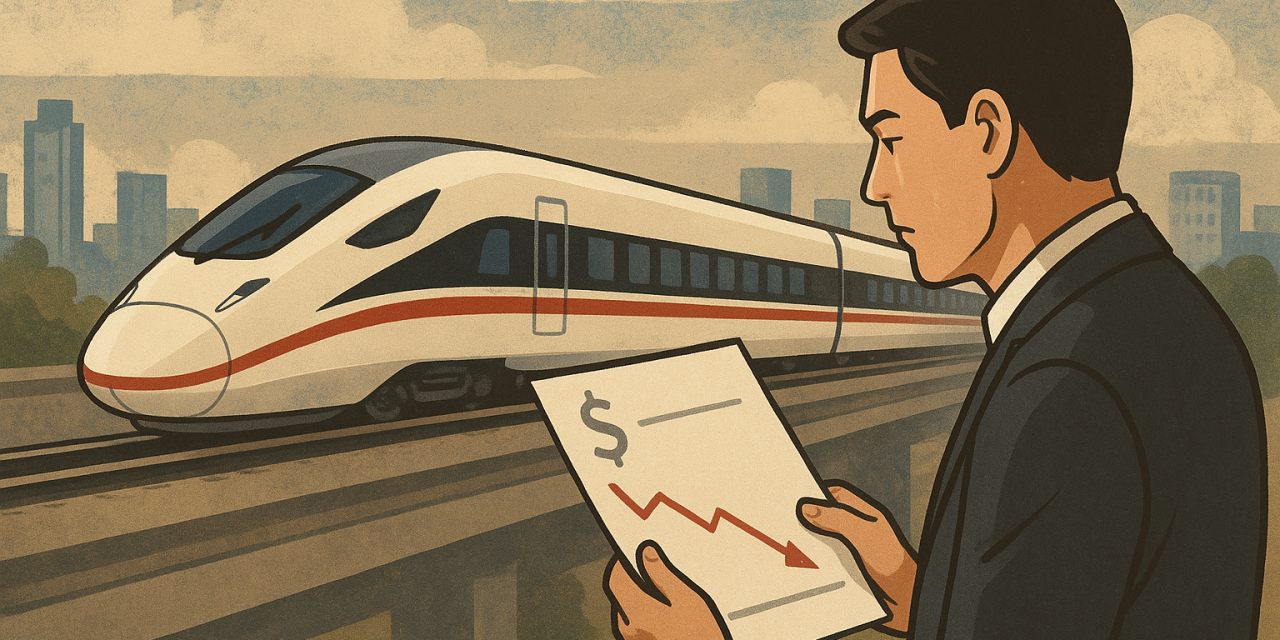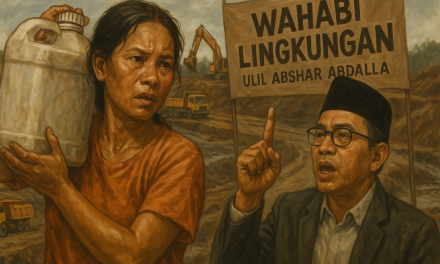Pada suatu pagi berhawa dingin di Bandung, kereta cepat Whoosh masih melesat mulus dari Tegalluar menuju Halim. Di dalam gerbong, suara roda hampir tak terdengar. Sebagian penumpang sibuk menatap gawai, sebagian lainnya mengabadikan pemandangan kota yang perlahan memudar ke balik dinding kaca.
Semua tampak baik–baik saja dari kursi kelas premium. Namun di balik pemandangan elegan itu, PT Kereta Api Indonesia (KAI) sedang memegang laporan keuangan yang mulai berwarna merah – bukan karena kesalahan penghitungan, melainkan karena kerugian yang terus mengalir dari proyek ambisius itu.
Ketika Ignasius Jonan memimpin, KAI pernah menjadi role model: perusahaan negara yang berhasil direformasi menjadi modern, disiplin, dan efisien. Ia membenahi jadwal, menghapus pungli, memperbaiki stasiun, bahkan mengubah wajah kereta ekonomi menjadi bersih dan ramah. Pada tahun-tahun itu, publik perlahan kembali percaya bahwa BUMN bukan sekadar mesin birokrasi tanpa arah.
 Kini, satu dekade kemudian, nama besar itu berhadapan dengan sebuah proyek yang secara politis membanggakan, tapi secara finansial menantang: Kereta Cepat Jakarta–Bandung.
Kini, satu dekade kemudian, nama besar itu berhadapan dengan sebuah proyek yang secara politis membanggakan, tapi secara finansial menantang: Kereta Cepat Jakarta–Bandung.
Pada semester pertama 2025 saja, kerugian dari Whoosh tercatat lebih dari Rp1 triliun. Jumlah itu seolah tidak besar bila dibandingkan dengan PDB nasional, tapi cukup untuk menggerus stabilitas kas PT KAI yang selama ini digunakan untuk menggerakkan layanan komuter, logistik, maupun revitalisasi perkeretaapian daerah.
“Bank bisa menunggu, gerbong kereta rakyat tidak bisa,” ujar seorang pejabat internal KAI yang enggan disebutkan namanya.
Ia tidak sedang berkelakar. Laporan keuangan terbaru menyebutkan bahwa beban bunga dan biaya operasional Whoosh sudah mengalir ke rekening PT KAI, menandakan bahwa beban kerugian tidak lagi abstrak – ia kini nyata, terasa di cash flow.
Jika semuanya berjalan sesuai rencana, trafik Whoosh akan meningkat, restrukturisasi pinjaman ke China Development Bank bisa dirampungkan, dan pendapatan non-tiket (seperti sewa ruang komersial dan pengembangan TOD) akan menjadi bantalan.
Dalam skenario terbaik itu, kerugian akan menurun dan KAI bisa kembali menatap ekspansi bisnis intinya.
Tapi bila target penumpang stagnan, dan moratorium terhadap bunga utang tak pernah datang, maka jalur rel yang dibanggakan itu lambat laun berubah menjadi lubang sunyi yang menyedot kas satu demi satu.
Seorang pengamat transportasi menyebutnya “paradoks infrastruktur” – dibangun untuk mempercepat ekonomi, tapi bisa memperlambat perusahaan pelaksananya bila tak dikelola cermat.
PT KAI belum bangkrut – dan bahkan masih jauh dari kata itu – tetapi ancaman ke arah sana bukan lagi hipotesis akademik. Pada 2026–2027, beban kerugian bisa menentukan apakah KAI dapat melanjutkan investasinya ke sektor-sektor yang lebih produktif, atau justru harus menunda semuanya demi menutupi defisit Whoosh.
Di Stasiun Halim, seorang petugas menutup pintu gerbong terakhir seraya memberi hormat. Senyum kecil terukir di wajahnya – mungkin karena bangga, mungkin juga karena setiap perjalanan kereta cepat menyimpan harapan.
Harapan bahwa suatu hari nanti, rel yang dibangun dengan kebanggaan ini benar-benar bisa dirayakan sebagai kemenangan, bukan sebagai beban yang dibayarkan dengan diam-diam oleh perusahaan yang pernah bangkit berkat kedisiplinan dan akal sehat.
Dan seperti halnya kereta, narasi ini masih berjalan. Tidak berhenti pada satu stasiun.